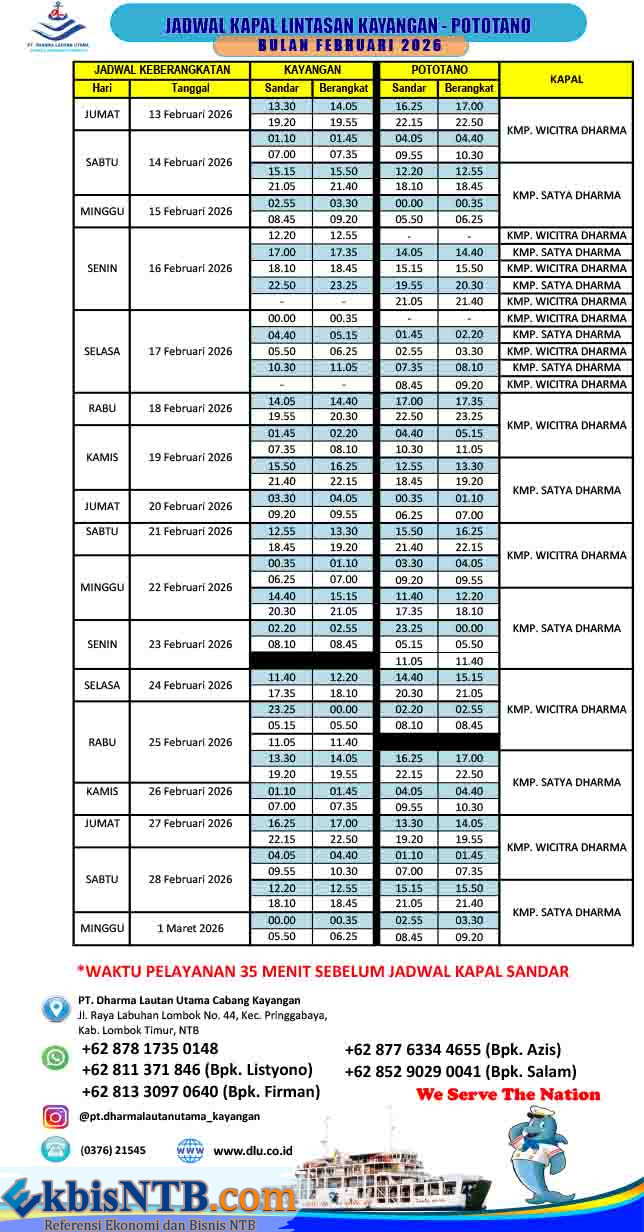Oleh Markum, Guru Besar Unram
Tulisan ini menelaah realitas peran senat dan proses pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri berstatus PTN BLU. Proses ini tidak hanya menjadi ajang pertimbangan akademik, tetapi juga arena tarik-menarik kepentingan yang mencerminkan dinamika politik kampus. Di sinilah idealisme keilmuan sering kali bernegosiasi dengan strategi dan kalkulasi kekuasaan dalam ruang demokrasi universitas.
Pemilihan rektor di perguruan tinggi negeri sering kali disebut sebagai puncak demokrasi akademik. Namun, di balik idealisme itu, tersembunyi realitas politik yang tak kalah kompleks dari panggung kekuasaan nasional. Senat universitas yang sejatinya dibentuk sebagai penjaga nilai-nilai akademik dan moral kelembagaan, dalam praktiknya condong berperan sebagai institusi yang melegitimasi terpilihnya rektor. Peran strategis senat menonjol pada masa-masa menjelang pemilihan rektor, ketika suara senat menjadi rebutan para calon rektor yang ingin memastikan dukungan formal untuk melangkah ke kursi tertinggi kampus. Setelah proses itu usai, fungsi senat cenderung beralih menjadi kelembagaan simbolik dan seremonial.
Dalam suasana kompetisi yang kental dengan kepentingan, ruang-ruang akademik perlahan bergeser menjadi arena lobi, negosiasi, dan bahkan transaksi. Tidak jarang, preferensi politik dan kedekatan personal lebih menentukan arah pilihan dibandingkan pertimbangan akademik atau rekam jejak integritas calon. Senat yang berafiliasi dengan rektor pemenang akan memperoleh posisi yang lebih menguntungkan, baik secara struktural maupun akademik. Hal ini menciptakan lingkaran kepentingan yang berulang dari satu periode kepemimpinan ke periode berikutnya.
Situasi ini semakin diperumit oleh komposisi suara yang tidak sepenuhnya otonom. Ketika suara menteri memiliki bobot hingga 35 persen, maka kontestasi menjadi pertarungan untuk memenangkan hati kementerian. Siapa yang mampu meraih restu politik di tingkat pusat, hampir pasti memiliki peluang besar untuk memenangkan pemilihan. Dalam kondisi demikian, pemilihan rektor bukan lagi sekadar ajang seleksi pemimpin akademik, melainkan refleksi dari dinamika politik kekuasaan yang menembus tembok universitas.
Dengan komposisi suara yang menetapkan 65 persen berasal dari senat universitas dan 35 persen dari kementerian, dinamika politik kampus pun tak terelakkan. Dalam ruang inilah kalkulasi strategis dan hitung-hitungan politis mulai dimainkan. Setiap calon rektor pasti berupaya mengamankan sedikitnya 51 persen suara sebagai tiket aman menuju kursi tertinggi kepemimpinan universitas.
Namun, siapa yang bisa menjamin bahwa suara yang tampak solid dalam satu kubu tidak akan berpindah arah di menit-menit terakhir? Dinamika politik kampus kerap cair, dan loyalitas sering kali bertahan sejauh kepentingan berjalan. Karena itu, mendapatkan dukungan menteri menjadi jalan paling aman. Masalahnya, suara menteri bukanlah hadiah yang jatuh dari langit—melainkan hasil dari jaringan, kedekatan, dan afiliasi politik yang kuat di lingkar kekuasaan. Di titik inilah, arena akademik mulai beririsan dengan gelanggang politik nasional.
Maka setiap calon rektor akan mengerahkan seluruh sumber daya yang dimilikinya untuk menembus lingkar pengaruh kementerian. Segala jalur komunikasi dibuka, dari pendekatan formal hingga diplomasi personal yang halus dan terukur. Siapa pun yang diyakini memiliki kedekatan atau daya kendali terhadap menteri segera menjadi target utama—sosok yang harus dirangkul, diyakinkan, bahkan mungkin “diinvestasikan” demi memastikan arah restu politik tidak melenceng dari harapan.
Jabatan rektor adalah posisi tertinggi di lingkungan universitas. Sebuah kursi yang memegang kendali atas arah kebijakan, sumber daya, dan wajah institusi di mata publik. Dari peran dan fungsinya, jabatan ini memang bersifat akademis, namun proses menuju ke sana justru sarat nuansa politis. Seperti dikatakan Clark Kerr (President University of California), seorang rektor bukan semata pemimpin akademik, melainkan mediator di antara kepentingan yang saling bersaing—akademik, politik, dan finansial. Tak heran, siapa pun yang berhasil mendudukinya akan berupaya untuk bertahan, menjaga pengaruh, dan memastikan jejaring dukungannya tetap solid sepanjang masa kepemimpinan. Kekuasaan adalah daya pesona paling menggoda (Henry Kissinger, 1973).
Pada akhirnya, dinamika politik dalam pemilihan rektor tidak bisa dilepaskan dari sistem yang dibentuk oleh kebijakan nasional tentang tata kelola universitas. Campur tangan negara dalam menentukan komposisi suara, peran senat, dan porsi kementerian telah melahirkan pola interaksi politik yang tidak terelakkan dalam konteks sistem tersebut. Perilaku seseorang untuk memenangkan pertarungan kekuasaan, dibentuk karena sistem yang diciptakan. Seperti dikatakan Machiavelli (1527), perilaku politik seseorang bukan hanya cermin dari tabiat pribadinya, tetapi juga dari sistem yang membentuknya. Dalam setiap arena kekuasaan, siapa pun akan belajar menyesuaikan diri dengan aturan yang diciptakan sistem itu sendiri, sebab di sanalah ukuran kemenangan ditentukan.
Pada titik inilah, demokrasi kampus dihadapkan pada tantangan mendasar: bagaimana menjaga keseimbangan antara kompetisi kekuasaan yang tak terelakkan dengan nilai-nilai etik dan akademik yang menjadi ruh universitas. Oleh karena itu, refleksi terhadap sistem dan perilaku politik dalam pemilihan rektor sejatinya bukan sekadar persoalan kepatuhan pada hukum atau kebijakan nasional, tetapi juga penting untuk penghormatan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan marwah akademis.