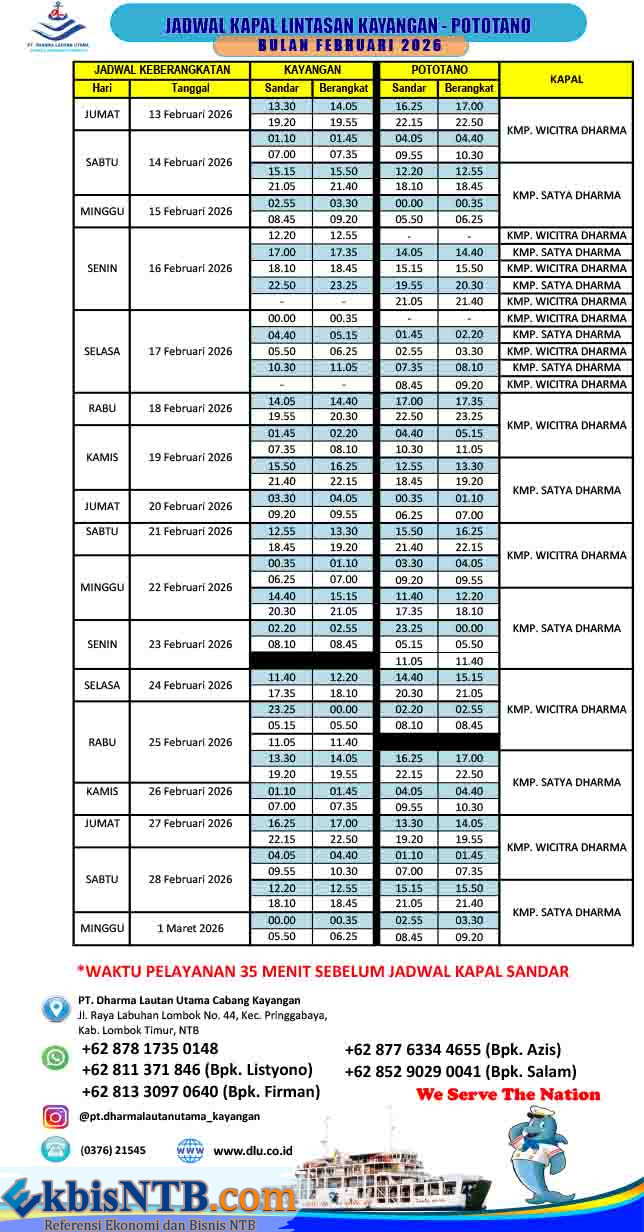Lombok (ekbisntb.com) – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyampaikan keberatan atas kebijakan pengenaan royalti musik di tempat usaha seperti restoran, kafe, dan hotel. Ketua PHRI NTB, Ni Ketut Wolini, menilai kebijakan ini tidak hanya membebani pelaku usaha di daerah, tetapi juga minim sosialisasi serta menyisakan banyak ketidakjelasan dalam implementasinya.
“Sekarang ini sudah ada yang membayar royalti musik, dan ada yang belum, karena kami sendiri belum paham mekanisme pembayarannya. Tidak ada sosialisasi yang jelas dari pusat maupun dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN),” tegas Wolini, Selasa, 5 Agustus 2025 usai mengikuti kegiatan di Kanwil Pajak DJP Nusra.
Minim Sosialisasi dan Tak Ada Cabang LMKN di Daerah
Wolini mengungkapkan bahwa pengusaha di daerah kesulitan mendapatkan informasi langsung dari LMKN karena lembaga tersebut tidak memiliki cabang di luar Jakarta. Akibatnya, pelaku usaha di NTB kebingungan ketika ingin berkonsultasi.
“Kalau hanya lewat telepon atau HP, itu tidak maksimal. Kami butuh pencerahan langsung. Bagaimana bisa kami patuh pada aturan kalau tidak ada yang memberikan arahan?” ungkapnya.
Skema Hitungan Royalti
Dinilai Memberatkan PHRI NTB menilai skema pengenaan royalti yang menghitung luas ruangan per meter persegi sangat tidak berpihak pada pelaku usaha, terutama di daerah yang masih berjuang bangkit dari berbagai krisis.
“Bayarnya memang sekali setahun, tapi tetap berat. Sekarang ini saja pengusaha belum pulih. Kami sudah dibebani pajak daerah, pajak pusat, sekarang ditambah royalti musik. Tidak balance,” tegasnya.
Wolini bahkan menyebut, total beban pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha bisa mencapai 30 persen dari pendapatan. Menurutnya, ini sangat besar dan bisa mematikan geliat usaha di sektor pariwisata dan kuliner.
PHRI Minta Revisi dan Pencerahan dari LMKN
Ketua PHRI NTB berharap pemerintah pusat maupun LMKN melakukan revisi terhadap kebijakan ini. Ia juga meminta LMKN segera turun ke daerah untuk memberikan pemahaman secara langsung.
“Jangan hanya ancaman pidana yang disampaikan. Undang-undangnya dibuat, tapi tidak ada pencerahan. Sedikit-sedikit pidana. Sementara kami di daerah masih berjuang, daya beli masyarakat juga menurun,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini PHRI NTB hanya bisa menunggu kejelasan terkait petunjuk teknis atau revisi undang-undang yang mengatur royalti musik di tempat usaha. “Saya sebagai Ketua PHRI saja belum pernah diajak bicara. Lalu kemana kami harus konsultasi?” ujarnya heran.
Usaha Kembali Lesu Setelah FORNAS
Wolini juga menggambarkan kondisi usaha di NTB yang belum stabil. Ia menyebut, pelaku usaha hanya sempat merasakan geliat ekonomi selama penyelenggaraan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS), setelah itu kembali sepi.
“Kemarin kami diselamatkan oleh FORNAS selama seminggu. Setelah itu, usaha kembali ‘tidur’. Sementara pajak tetap harus dibayar tinggi, dan kini ditambah royalti. Anggota kami resah dengan kondisi seperti ini,” katanya.
PHRI Imbau Pengusaha Tidak Putar Musik Jika Terlalu Berat
Sebagai bentuk respons atas kebijakan yang dirasa tidak berpihak, PHRI NTB bahkan mengimbau para pelaku usaha untuk tidak memutar musik di tempat usahanya jika merasa terbebani biaya royalti.
“Daripada bermasalah, lebih baik tidak usah memutar lagu. Bisa jadi seperti Mie Gacoan yang jadi tersangka karena royalti. Semua lagu kena royalti sekarang,” tegas Wolini.
Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa para pelaku usaha di NTB telah mengalami berbagai pukulan sejak 2018. Mulai dari gempa bumi, pandemi Covid-19, hingga tekanan ekonomi akibat efisiensi dan kebijakan yang terus berubah.(bul)