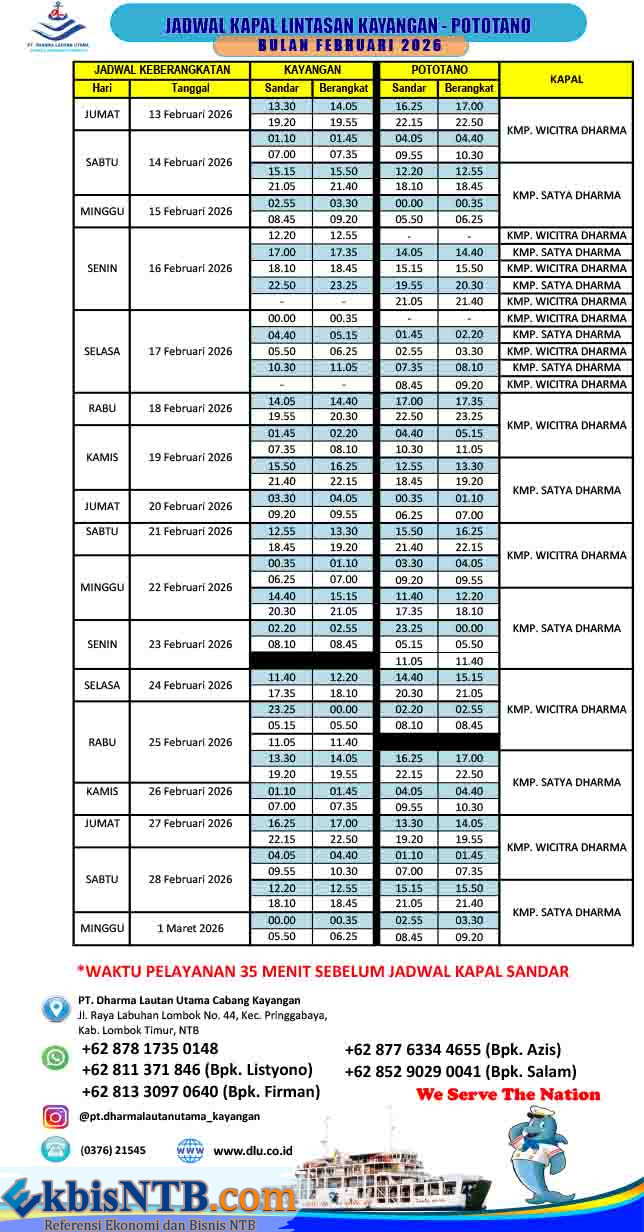Lombok (ekbisntb.com) – Di balik kemudahan layanan transportasi daring yang dinikmati sebagian masyarakat Kota Mataram, tersembunyi realitas pahit yang kian menggerogoti kehidupan ribuan pengemudi ojek daring (ojol).
Sebuah ironi pembangunan di mana inovasi teknologi justru menghadirkan jurang ketidakadilan bagi para pekerjanya. Menjadi Ojol sekarang ibaratnya seperti sapi perah, hanya sedikit manfaatnya didapat, sisanya mengalir ke pendapatan aplikator. Apa daya, tidak ada pilihan, ditengah susahnya mendapat pekerjaan.
Media ini menghubungi salah satu aplikator ojek terbesar, Selasa pagi, 20 Mei 2025. Pesan ojeknya dari apliasi responnya sangat cepat, sudah dapat pengemudinya.
Di aplikasi biaya perjalanan dan administrasi yang harus dibayar Rp25 ribu. Sepanjang perjalanan, pengemudi ini lalu bercerita, realita kini menjadi ojek yang dikendalikan aplikasi.
Dari ceritanya, tergambar potret buram industri ojol di Mataram saat ini jauh lebih mengkhawatirkan dibandingkan masa-masa sulit sebelum pandemi Covid-19.
Fenomena “kebablasan” jumlah pengemudi menjadi sorotan utama. Menurutnya, saat ini sudah lebih dari 6.000 ojek online yang memadati jalanan Mataram, persaingan untuk mendapatkan orderan semakin sengit.
Perbandingan yang sangat mencolok antara ketersediaan pengemudi dan permintaan pelanggan. “Bayangkan saja, kalau dalam sehari hanya ada seribu pelanggan, jumlah itu harus dibagi rata oleh enam ribuan ojek. Dulu, sebelum Covid-19 saya bisa dengan mudah mendapatkan 30 orderan sehari, sekarang di bawah 10 saja sudah sangat bagus,” ungkapnya.
Penurunan drastis jumlah orderan berbanding lurus dengan merosotnya pendapatan para ojek online. Jika sebelum pandemi seorang pengemudi bisa mengantongi hingga Rp 4 juta per bulan, kini angka tersebut terjun bebas menjadi hanya sekitar Rp 600 ribu. Pendapatan harian pun mengalami nasib serupa, dari Rp 300 ribu dulu, kini menjadi hanya sekitar Rp 40 ribu. Kondisi ini jelas mengancam stabilitas ekonomi keluarga para pengemudi.
Kepada media ini, juga dikisahkan betapa beratnya situasi ini.
“Dulu, dengan pendapatan yang lumayan, saya berani mengambil kredit rumah subsidi. Cicilannya satu juta, masih ada sisa banyak. Sekarang, pendapatan dari ojol saja tidak cukup untuk membayar cicilan rumah. Belum lagi kebutuhan hidup lainnya,” tuturnya.
Untuk menanggulangi pengeluaran bulanan keluarga, menurut sumber ini, istrinya harus bekerja sebagai asisten rumah tangga, meninggalkan anak-anak mereka demi menjaga cicilan rumah tetap berjalan. Sebuah pilihan pahit yang mencerminkan betapa terdesaknya kondisi ekonomi keluarga pengemudi ojol saat ini.
Lebih lanjut, narasumber menyoroti sistem bagi hasil yang diterapkan oleh perusahaan aplikasi sebagai akar permasalahan lainnya.
“Kalau tarif di aplikasi Rp 22 ribu, yang kami terima hanya Rp 7.800. Potongan yang sangat besar ini membuat kami semakin sulit untuk mendapatkan penghasilan yang layak,” keluhnya.
Transparansi dan keadilan dalam sistem pembagian pendapatan ini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.
Ironisnya, di tengah keluhan para pengemudi lama, perusahaan aplikasi justru terus membuka pendaftaran pengemudi baru dalam jumlah besar pasca-pandemi. Bahkan, untuk dapat bergabung, calon pengemudi harus membayar biaya pendaftaran yang cukup signifikan, berkisar antara Rp 700 ribu hingga Rp 1,1 juta. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai motif perusahaan dan dampaknya terhadap kesejahteraan pengemudi yang sudah ada.
“Mengapa perusahaan terus menambah jumlah pengemudi. Padahal jumlahnya sudah banyak sekali sekarang. Dan orang rela bayar untuk daftar jadi ojek ini, bayarnya ada yang sampai Rp1,1 juta,” urainya.
Ketidakberdayaan para pengemudi semakin diperparah oleh kebijakan perusahaan yang represif terhadap kritik dan protes.
“Kami tidak berani macam-macam. Kalau protes kebijakan, akun kami bisa langsung disanksi, bahkan tidak dikasih orderan sama sekali. Sementara, mencari pekerjaan lain di Mataram ini juga tidak mudah,” ungkapnya.
Ketakutan akan kehilangan mata pencaharian membuat para pengemudi enggan menyuarakan keluhan mereka secara terbuka, termasuk dalam aksi-aksi demonstrasi yang terkadang terjadi. “Makanya saya tidak berani ikut demo. Takut disanksi. Lebih baik dijalani saja,” imbuhnya.
Kisah narasumber ini membuka mata kita pada kompleksitas permasalahan yang dihadapi para pengemudi ojol di Mataram. Lebih dari sekadar persaingan pasar, terdapat isu-isu mendasar terkait regulasi, sistem bagi hasil yang tidak transparan, dan lemahnya posisi tawar pengemudi di hadapan perusahaan aplikasi. Fenomena ini juga memunculkan pertanyaan etis mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan mitra kerjanya.
Harapan terakhir para pengemudi kini tertuju pada pemerintah daerah dan pusat. Mereka berharap adanya regulasi yang lebih berpihak pada kesejahteraan pengemudi ojol, termasuk penataan jumlah pengemudi, transparansi sistem bagi hasil, dan mekanisme perlindungan bagi para pekerja informal ini.
Tanpa intervensi yang konkret, mimpi para pengemudi ojol di Mataram untuk mendapatkan penghidupan yang layak akan terus menjadi ilusi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital. Pemerintah perlu hadir sebagai mediator dan regulator yang adil, memastikan bahwa inovasi teknologi tidak mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan para pekerja di garda terdepan.(bul)